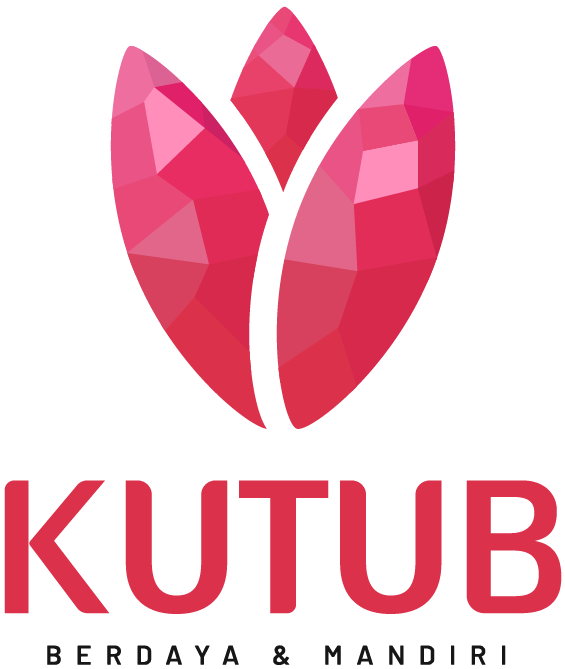Kutub.co – Di sebuah kamar, seorang anak bermain gim online dengan wajah penuh tawa. Avatar warna-warni melompat di layar. Ada teman-teman baru yang menyapa ramah. Mereka membantu saat ia tertinggal, menghibur saat kalah, bahkan memberikan hadiah virtual supaya permainan semakin seru. Tapi keramahan itu bisa berubah menjadi jebakan ketika obrolan santai bergeser pelan:
“Kamu umur berapa?”
“Sekolah di mana?”
“Ayo pindah ke DM, lebih enak ngobrolnya.”
“Foto kamu dong, biar makin akrab.”
“Aku pikir semua orang ramah,” ujar Ai Masruroh, pemain gim online pemula. “Tapi lama-lama ada yang nanya hal pribadi terus. Aku jadi takut dan menjauh.”
Ia juga pernah melihat deepfake, wajah seseorang ditempel ke video yang bukan dirinya. “Kalau itu bisa menimpa orang lain, berarti kita semua bisa jadi korban,” katanya.
Bagi orang tua, ruang digital seperti petak buta yang penuh teka-teki.
“Saya ingin anak merasa aman, bukan diawasi,” kata Betty Herlina, seorang ibu yang waspada. “Tapi voice chat, avatar anonim… kita nggak tahu siapa di balik layar.”
Untuk memastikan keamanan anaknya tanpa merasa diawasi, Betty memulainya dengan obrolan santai: “Ada teman baru hari ini?”
Betty berharap informasi keamanan digital tak lagi tersebar acak dan teknis. “Kalau kita bingung, bagaimana mau melindungi?”
Dari sisi industri, Khemal Andrias, CEO Next Generation Indonesia (NXG), menyebut bahwa pelaku grooming tak pernah datang sebagai ancaman. Mereka datang sebagai “teman terbaik.”
“Mulainya dari mabar,” jelasnya. “Terus pujian: ‘Kamu jago banget’. Lalu gift seperti diamond atau skin. Pelaku membangun ketergantungan emosional.” Ketika korban merasa aman, pelaku mengajak pindah ke ruang pribadi. Saat itulah semua kontrol platform berhenti.
Jika deepfake masuk ke proses ini, korban bukan hanya takut tapi merasa tak punya bukti kebenaran.
“Korban harus membuktikan bahwa itu bukan wajah mereka,” ujar Khemal. “Itu menyakitkan. Sudah jadi korban, malah harus membela diri.” Apa yang disampaikan Khemal adalah salah satu bentuk penyalahan terhadap korban yang memicu reviktimisasi, sebuah hal yang kerap terjadi dalam budaya perkosaan.
Dalam konteks platform, Khemal juga menegaskan bahwa alih-alih bersikap reaktif, dia mengharapkan platform bisa lebih proaktif dengan memperlakukan:
- Penerapan safety by design; Ini adalah konsep di mana fitur keamanan bukan sekadar tempelan, tapi ditanam sejak aplikasi dibuat. Misal untuk gim pemisahan matchmaking berbasis usia. Anak-anak tidak diperkenankan main di server orang dewasa. Kemudian secara default voice chat harusnya Off dan hanya bisa diaktifkan oleh orang tua. Atau pemanfaatan AI untuk mendeteksi teks atau audio yg menunjukan pola-pola grooming (contoh; “jangan bilang orang tuamu). Untuk sosial media: verifikasi identitas ketat; tidak cukup menggunakan ID saja, tapi juga menggunakan biometrik (wajah langsung) untuk mengaktifkan fitur sensitif. Fitur lain di sosial media bisa menggunakan watermark Akal Imitasi (AI) otomatis bila itu dibuat oleh AI. Agar user tidak tertipu.
- Sistem laporan lintas platform; Pelaku grooming sering kali mencari mangsa di game, lalu mengajak korban pindah ke media sosial pribadi (Discord, WhatsApp, Instagram) untuk melancarkan aksinya tanpa pantauan moderator game. Platform game dan media sosial harus membangun protokol berbagi data (seperti Tech Coalition).
- Platform secara serius melakukan penghapusan Konten “Nudify” dan Deepfake Pornografi
- Mempersulit Transaksi Mata Uang Game (In-Game Gift); Salah satu modus utama grooming adalah mengiming-imingi anak dengan skin, diamond, atau robux. Misalnya; Mewajibkan verifikasi tambahan (seperti PIN orang tua atau delay waktu 24 jam) saat seorang akun dewasa ingin memberikan “gift” kepada akun yang terdeteksi sebagai anak di bawah umur yang baru dikenal (belum berteman lama).
- Edukasi Aktif atau penerapan community guideline secara realtime. Misal; Jika sistem mendeteksi pengguna hendak mengirim foto wajah berkualitas tinggi ke orang asing di DM, maka munculkanlah pop-up peringatan: “Foto ini bisa disalahgunakan untuk Deepfake.
Ada fakta yang menguatkan kekhawatiran ini.
Laporan SAFEnet mencatat 665 aduan kasus KBGO pada kuartal II 2025, naik dari 465 pada periode sama 2024. Kasus deepfake dan morphing juga meningkat tajam dalam dua tahun terakhir. Mayoritas pelapor adalah perempuan usia 18–25 tahun, sekitar 61,8% dari aduan.
Data Komnas Perempuan menunjukkan 1.791 kasus KBGO pada 2024, naik 48% dari tahun sebelumnya. Bahkan beberapa penelitian menemukan bahwa laporan pada triwulan pertama 2024 melonjak empat kali lipat dibanding periode serupa 2023.
Namun angka itu belum menggambarkan keseluruhan situasi. Sebagian besar kasus tidak pernah dilaporkan, tenggelam dalam ketakutan, rasa malu, dan stigma.
Menurut Hana Nabila Putri dari Srikandi KBGO, persoalan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi warisan budaya.
“Masyarakat belum punya literasi keamanan yang memadai. Banyak yang bahkan tidak tahu 2FA itu apa,” katanya. “Akses informasinya terbatas, lebih banyak ditemukan oleh orang yang sudah melek teknologi.”
Hana juga menambahkan bahwa syarat dan ketentuan, khususnya tentang keamanan yang diberikan oleh platform terlalu panjang dengan kurangnya minat membaca masyarakat Indonesia, hal itu seringkali diabaikan dan hanya dilewati saja.
Hana juga menekankan bahwa patriarki membuat perempuan dan anak lebih rentan:
“Kesadaran mengenai tubuh dan hak pribadi tidak diajarkan sejak kecil. Jadi saat kekerasan terjadi, banyak yang tidak sadar bahwa itu kekerasan.”
Hana juga membagikan temuan komunitasnya mengenai sebuah gim online simulasi hubungan yang rentan objektifikasi dimana pemainnya bisa membuat avatar dengan fetish yang dia sukai. Tanpa dibatasi usia dan jenis kegiatan apa yang dilakukan.
Sebuah platform yang dibuat untuk siapapun itu kini menjadi sarang dari orang-orang yang memiliki kelainan fantasi seksual pada anak-anak. Kurangnya aturan dalam moderasi konten gim online menjadikan ini terus tumbuh dan terabaikan.
Korban sering kali menyalahkan dirinya sendiri. “Padahal yang salah adalah pelaku dan sistem yang membiarkan,” tegas Hana. Namun, ia punya harapan besar: kolaborasi non-kepentingan.
Ia membayangkan platform digital bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas:
“Kita harus membuat ruang edukasi yang terstruktur, seperti lokakarya dan penyuluhan rutin di sekolah. Anak belajar langsung soal keamanan digital dari sumber yang mudah dipahami.”
Hana meyakini bahwa keamanan digital harus menjadi budaya, bukan sekadar solusi setelah terluka.
Ketika literasi keamanan rendah, ketika perempuan tidak diberi ruang menyuarakan batasan, ketika platform belum didesain aman sejak awal, maka dunia digital dengan mudah berubah menjadi ladang perburuan.
“Profil bisa palsu, foto bisa ambil dari mana aja,” kata Ai. “Dan kalau sudah bocor, kita cuma bisa pasrah.”
Sistem sekarang masih membuat korban menjadi penjaga dirinya sendiri. Namun cerita ini belum ditutup. Ada ruang untuk kita memperbaikinya dengan cepat.
“Kita harus proaktif,” ujar Khemal. “Menunggu korban muncul adalah kegagalan.”
Kemudian Betty menegaskan, “Anak bukan hanya butuh gadget,Tapi juga alat untuk merasa aman.”
“Kalau literasi digital dan kesadaran gender tidak dimulai sedari dini, korban akan terus menyalahkan dirinya sendiri.” Kata Hana menambahkan konteks budaya dan sistem yang harus diubah.
Teknologi bisa memajukan hidup manusia. Tapi keamanan manusia harus lebih maju dari teknologi. Wajah kita tidak boleh dicuri. Kepercayaan kita tidak boleh diperdagangkan. Dan dunia bermain kita tidak boleh menjadi perangkap. (Dianah Nisa) [*]