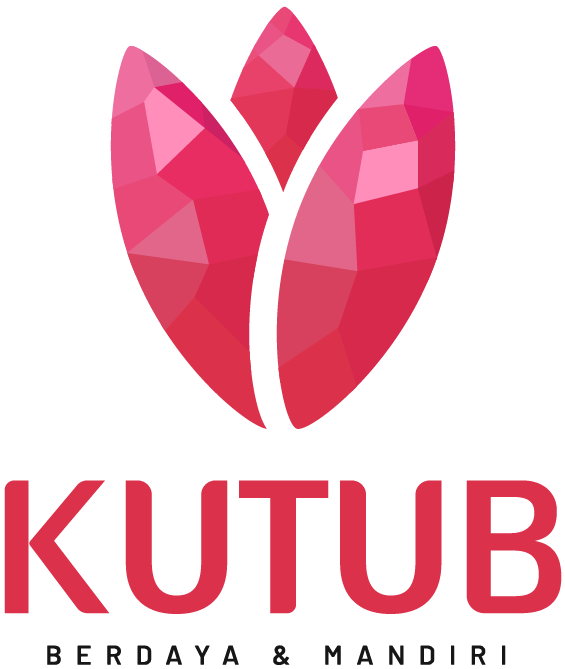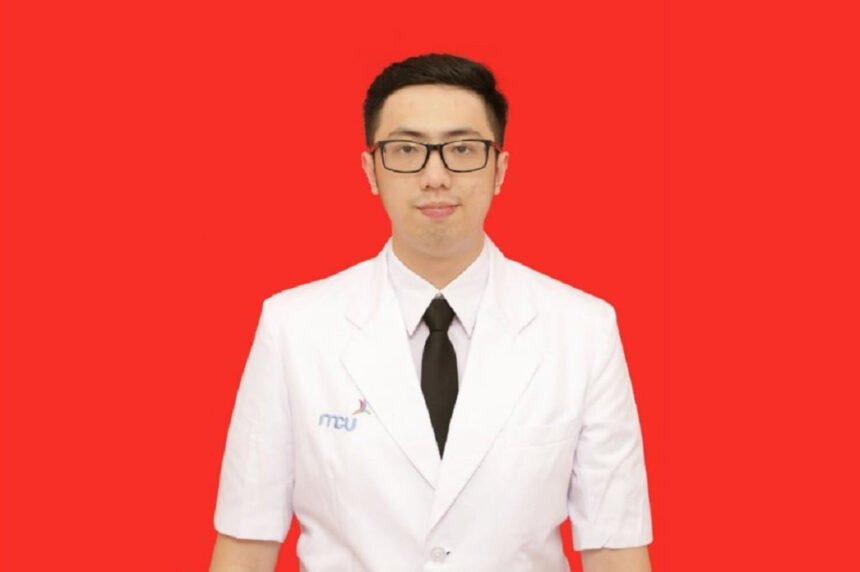“Bandung romantis ya kalau hujan…”
Potongan kalimat itu ramai di media sosial ketika hujan turun di Kota Bandung, bahkan ada yang menjadikannya sebagai semacam mantra estetika kota. Tapi bagi sebagian warga perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten misalnya, kalimat tersebut terdengar seperti lelucon pahit. Sama sekali tidak romantis saat hujan turun. ketika jalan-jalan berubah menjadi sungai dadakan, dan ketika orang-orang harus menata ulang rasa aman mereka hanya karena cuaca bekerja sedikit lebih keras dari biasanya.
Ada jarak yang barangkali nyata antara Bandung yang dirayakan di internet dan Bandung yang ditempati ribuan orang dengan kesiapsiagaan setiap kali musim hujan datang. Rania misalnya, nama yang coba disamarkan dan berbagi pengalamannya menghadapi banjir yang berkepanjangan.
Sore itu, ketika hujan turun cukup lama, Rania hendak pulang dari kerja dan berubah menjadi siksaan mental. Bukan cuma karena macetnya tidak bergerak, tapi karena tubuh yang sudah lelah dipaksa menanggung cemas tambahan: apakah air naik? Apakah jalan terputus? Apakah aku akan sampai rumah atau terjebak sampai larut? dan yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa besok paginya pun aku harus mengulang lagi drama yang sama.
Bangun pagi dengan badan yang belum pulih, lalu bertarung dengan macet yang muncul bukan karena jumlah kendaraan semata, tetapi karena banjir memutus akses, membuat rute kacau dan memaksa ribuan orang bertumpuk di jalur sempit yang tidak dipersiapkan untuk keadaan darurat. Rasanya seperti hidup dalam ritme yang tidak pernah memberi ruang bernapas.
Kemacetan itu bukan sekadar perjalanan tersendat. Tapi juga tekanan mental yang nyata: frustasi yang menempel, kecemasan yang mengendap, ketidakpastian yang membuat kepala terus berputar. Sementara di media sosial, Bandung masih disebut romantis ketika hujan turun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan betapa rapuhnya kota dan betapa beratnya beban psikologis yang ditanggung warganya.
Lalu apa solusi untuk pemerintah? Tidak cukup hanya menurunkan tim saat banjir sudah datang. Kita butuh perubahan struktural yang memihak warga, bukan sekadar proyek musiman yang selesai saat kamera mati.
Pertama, penataan ulang tata ruang. Pemerintah harus berhenti memberi izin pembangunan di kawasan yang sudah jelas tidak punya daya dukung. Ruang terbuka hijau yang hilang harus diganti, bukan diganti alasan.
Kedua, perbaikan drainase skala besar yang bukan sekadar tambal sulam. Drainase yang terintegrasi dengan sungai, perumahan, dan kawasan industri akan jauh lebih efektif daripada proyek perbaikan kecil yang diulang setiap tahun tanpa hasil.
Ketiga, sistem mitigasi lalu lintas saat banjir harus direncanakan sebelum bencananya terjadi. Ini bukan soal memperbanyak petugas di jalan; ini soal manajemen rerouting yang jelas, aplikasi informasi yang transparan, dan skenario transportasi yang siap pakai.
Keempat, pemerintah harus mulai memasukkan kesehatan mental dalam paradigma kebijakan bencana. Banjir bukan hanya soal logistik dan evakuasi; ini soal keselamatan psikis. Pemerintah bisa menyediakan hotline psikososial, ruang pemulihan, hingga kampanye edukasi untuk mengurangi stigma dan membantu warga mengelola kecemasan.
Kota yang sehat bukan hanya kota yang tidak banjir, tapi kota yang tidak membuat warganya merasa seperti harus bertahan hidup setiap kali hujan datang.
Karena sejujurnya, Bandung akan benar-benar romantis jika warganya aman, tenang dan tidak merasa sendirian menanggung beban yang seharusnya dipikul bersama oleh pemerintah.