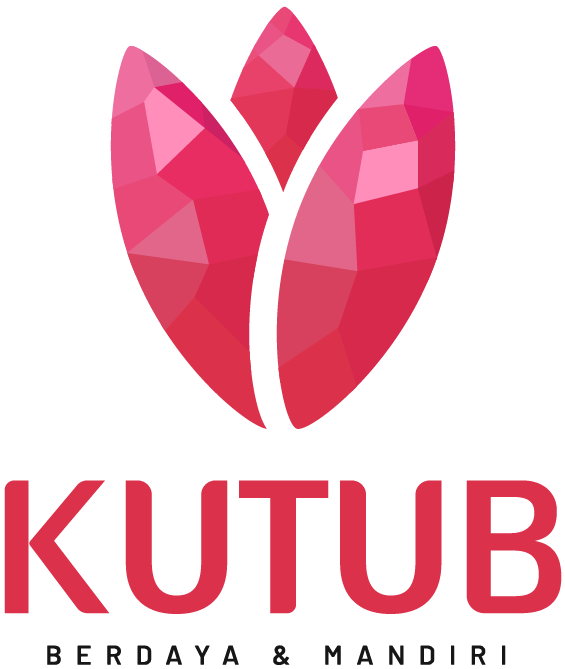Santri selalu identik dengan ketenangan, bukan karena hidup mereka bebas dari tekanan. Akan tetapi karena mereka belajar menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak. Dalam ritme pesantren yang sederhana, mereka membangun keseimbangan antara belajar, beribadah dan hidup bersama.
Pada hal inilah, sesungguhnya letak inti dari kesehatan mental: kemampuan menjaga harmoni antara pikiran, perasaan dan makna. Sebagaimana yang dikemukakan Dr. Faiz, “Keikhlasan adalah kunci untuk menemukan ketenangan jiwa.”Pernyataan ini mengingatkan bahwa ketenangan batin bukan semata hasil bebas dari masalah, tetapi hasil dari sikap hati yang rendah, terbuka, dan rela menerima keadaan. Di lingkungan pesantren, sikap semacam ini dapat terasah melalui rutinitas zikir, muraqabah, dan ukhuwah yang bukan hanya ibadah ritual, melainkan praktik hidup yang menumbuhkan kesadaran diri.
Pada momen Hari Santri, kita sering terjebak pada narasi heroik yang menempatkan santri sebagai penjaga moral bangsa. Namun jarang kita menyingkap sisi lain: bagaimana kehidupan pesantren mengajarkan kesadaran diri dan kesehatan jiwa yang sejati. Dunia santri bukan sekadar tempat belajar agama, melainkan ruang pendidikan batin; tempat manusia berlatih memahami dirinya dalam relasi dengan Tuhan dan sesama.
Konsep ini sejalan dengan gagasan psikolog humanistik Abraham Maslow tentang self-actualization, puncak dari kebutuhan manusia yang hanya dapat dicapai ketika seseorang memahami makna hidupnya. Dalam pesantren, aktualisasi diri bukan berarti mengejar pencapaian pribadi, tetapi menemukan ketenangan dalam pengabdian. Itulah yang oleh Al‑Ghazali disebut sebagai sakinah, kedamaian yang lahir dari jiwa yang mengenal sumbernya.
Namun, di balik romantisme itu, realitas psikologis di lingkungan madrasah dan pesantren juga menyimpan paradoks.
Beberapa santri, terutama di usia remaja menghadapi tekanan akademik, rasa rindu rumah, hingga tuntutan moral yang tinggi. Kesehatan mental mereka sering kali diuji dalam diam. Dalam konteks inilah, madrasah berbasis pesantren perlu melihat kesehatan mental bukan sebagai isu tambahan, melainkan sebagai bagian dari pendidikan integral: mendidik akal, hati, dan emosi secara seimbang. Menjadikan madrasah sebagai ruang sehat mental berarti menghadirkan lingkungan yang memanusiakan. Artinya, siswa tidak hanya dinilai dari hafalan dan prestasi, tetapi juga dari kemampuan mereka mengenali dan mengelola emosi.
Guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendengar dan seluruh warga madrasah dari kepala sekolah hingga teman sebaya menjadi bagian dari jejaring dukungan psikologis yang hidup.
Kesehatan mental dalam perspektif Islam bukan sekadar bebas dari gangguan jiwa, tetapi kemampuan menjaga keseimbangan (mizan) antara dunia lahir dan batin. Ketika seorang santri mampu menangis dalam doa dan tersenyum di tengah ujian, ia sedang mempraktikkan keseimbangan itu.
Dalam hal ini spiritualitas menjadi bentuk terapi paling alami: ia tidak meniadakan rasa sakit, tetapi memberi makna pada penderitaan.Hari Santri karenanya bisa dimaknai sebagai ajakan untuk menata kembali cara kita memahami pendidikan keagamaan. Bahwa mendidik santri tidak cukup hanya menguatkan iman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri, empati, dan kemampuan untuk merawat kesehatan jiwanya sendiri. Pesantren bisa menjadi model komunitas spiritual yang sadar mental, bukan karena mengadopsi teori Barat, tapi karena nilai-nilai Islam sudah lama mengajarkannya: tawakkal, ikhlas, ukhuwah dan rahmah.
Pada akhirnya, ketenangan jiwa seorang santri bukan hasil dari kehidupan tanpa badai, tetapi kemampuan menautkan setiap badai pada doa. Dan mungkin, dalam dunia yang semakin bising oleh tuntutan produktivitas dan citra, dunia santri sedang mengajarkan pada kita satu hal sederhana: bahwa menjaga kesehatan mental adalah cara lain untuk menjaga iman.