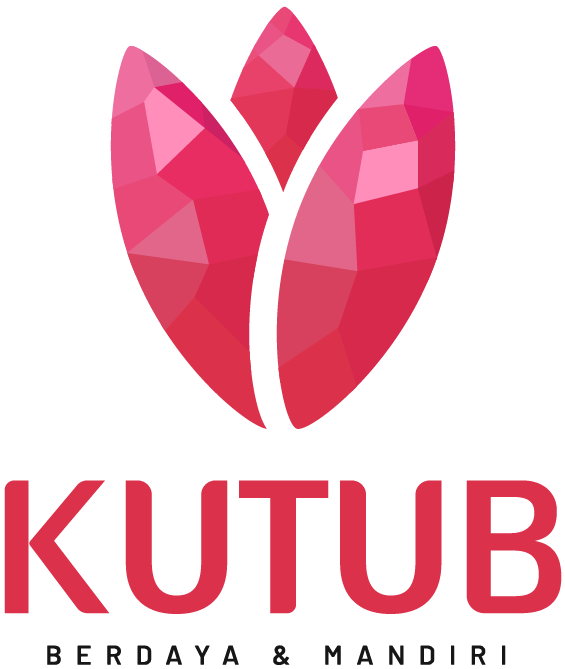Kutub.co – Self-care bukan ritual estetik, apalagi bentuk kemewahan emosional. Ia adalah praktik sadar untuk menjaga fungsi diri tetap berjalan secara mental, emosional, dan Self-care bukan ritual estetik, apalagi bentuk kemewahan emosional. Ia adalah praktik sadar untuk menjaga fungsi diri tetap berjalan secara mental, emosional, dan fisik di tengah kondisi yang sering kali tidak ideal. Self-care lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari pengakuan bahwa manusia memiliki batas. Dalam perspektif kesehatan mental, merawat diri berarti mampu mengenali tanda kelelahan, stres, dan emosi yang menumpuk, lalu meresponsnya secara proporsional. Bukan untuk menghapus masalah, tetapi mencegah tekanan kecil berkembang menjadi kelelahan yang merusak. di tengah kondisi yang sering kali tidak ideal.
Self-care lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari pengakuan bahwa manusia memiliki batas. Dalam perspektif kesehatan mental, merawat diri berarti mampu mengenali tanda kelelahan, stres, dan emosi yang menumpuk, lalu meresponsnya secara proporsional. Bukan untuk menghapus masalah, tetapi mencegah tekanan kecil berkembang menjadi kelelahan yang merusak.
Masalahnya, self-care kerap disalahartikan sebagai kewajiban untuk terus “menjadi versi terbaik diri sendiri”. Padahal, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan ketika seseorang mampu mengelola stres kehidupan sehari-hari, berfungsi secara produktif, dan berkontribusi pada lingkungannya. Kata kuncinya bukan mengalahkan tekanan, melainkan mengelola. Karena itu, self-care yang realistis sering kali tidak terlihat heroik berhenti sejenak sebelum runtuh, membatasi tuntutan orang lain atas energi kita, atau mengakui bahwa hari ini kita tidak sanggup. Ia tidak membuat hidup bebas masalah, tetapi memberi ruang agar seseorang tidak kehilangan dirinya sendiri.
Pemahaman inilah yang lama tidak dimiliki Ririn (bukan nama sebenarnya). Ia sampai pada satu kesimpulan yang terdengar dewasa, namun diam-diam melelahkan kalau ingin bertahan, ia harus selalu kuat.
Ririn bekerja, mengurus keluarga, merespons pesan dengan cepat, tetap hadir di pertemanan, dan berusaha tidak merepotkan siapa pun dengan ceritanya. Saat lelah, ia menamainya “kurang bersyukur”. Saat sedih, ia menyebutnya “cuma capek”. Masalahnya, rasa capek itu tidak pernah benar-benar pergi.
Suatu malam, Ririn duduk di kamar dengan lampu mati. Bukan karena dramatis, melainkan karena tidak ingin apa pun. Ia tidak menangis, tidak juga panik hanya kosong. Di titik itu, ia sadar bahwa yang selama ini ia sebut “kuat” ternyata hanyalah menunda runtuh.
Pola seperti ini bukan hal asing di Indonesia. Banyak orang terutama perempuan dibesarkan dengan gagasan bahwa merawat diri berarti tahan dulu, nanti juga biasa. Padahal, menurut psikolog klinis Liza Marielly Djaprie, kemampuan bertahan tanpa jeda justru berisiko mendorong kelelahan emosional kronis. Ia menekankan bahwa kesehatan mental bukan diukur dari seberapa lama seseorang sanggup menahan beban, melainkan dari kesadarannya mengenali dan menghormati batas diri.
Ririn mulai memahami itu ketika tubuhnya memberi sinyal yang tak bisa diabaikan: sulit tidur, mudah tersinggung, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu ia sukai. Tidak ada krisis besar. Justru di situlah letak bahayanya. Banyak orang mengira masalah mental harus selalu dramatis agar dianggap valid, padahal kelelahan yang sunyi sering kali lebih merusak.
Di titik ini, self-care sering kembali disalahpahami. Ia direduksi menjadi mandi air hangat, journaling estetik, atau liburan singkat. Semua itu tidak keliru, tetapi tidak cukup. Self-care yang realistis seperti yang perlahan dipelajari Ririn jauh lebih sederhana dan jujur.
Ia memulainya dari hal yang tidak populer mengizinkan dirinya berkata, “Aku lagi tidak sanggup.”
Kadang coping skill Ririn hanya berupa berhenti membalas pesan selama satu jam tanpa rasa bersalah. Kadang hanya menarik napas lebih pelan saat dadanya sesak, alih-alih memaksa diri untuk selalu berpikir positif. Ia mulai belajar membedakan mana masalah yang perlu diselesaikan, dan mana emosi yang cukup dirasakan.
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menekankan bahwa coping skill bukan selalu strategi besar atau perubahan hidup drastis. Ia justru sering hadir sebagai kemampuan kecil yang konsisten untuk menurunkan tekanan psikologis. Mengistirahatkan diri sebelum benar-benar habis adalah bagian dari keterampilan itu bukan tanda kegagalan.
Ririn tidak tiba-tiba menjadi tenang. Ia masih lelah, masih kadang ingin menghilang sebentar dari dunia. Bedanya, kini ia tidak lagi memusuhi dirinya sendiri karena itu. Ia belajar bahwa merawat diri bukan berarti berhenti peduli, melainkan berhenti memaksa.
Pada akhirnya, self-care bukan tentang menjadi lebih tahan banting, melainkan berhenti mengorbankan diri demi citra “baik-baik saja”. Dalam masyarakat yang terbiasa memuji ketahanan tanpa pernah bertanya tentang luka, merawat diri adalah tindakan sadar untuk memutus siklus kelelahan yang dinormalisasi. Ia tidak menyelesaikan semua persoalan, tetapi memberi seseorang cukup ruang untuk tetap utuh sebagai manusia dengan lelahnya, batasnya, dan ketidaksempurnaannya. Dari titik itulah, kemampuan bertahan yang lebih sehat justru bisa tumbuh.