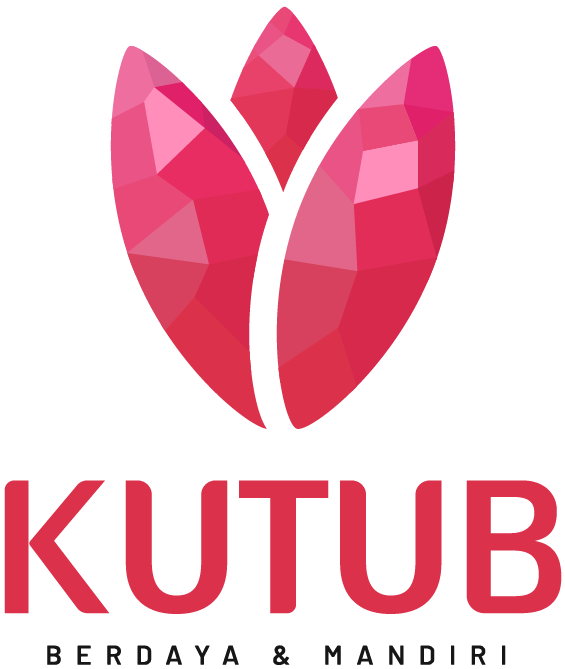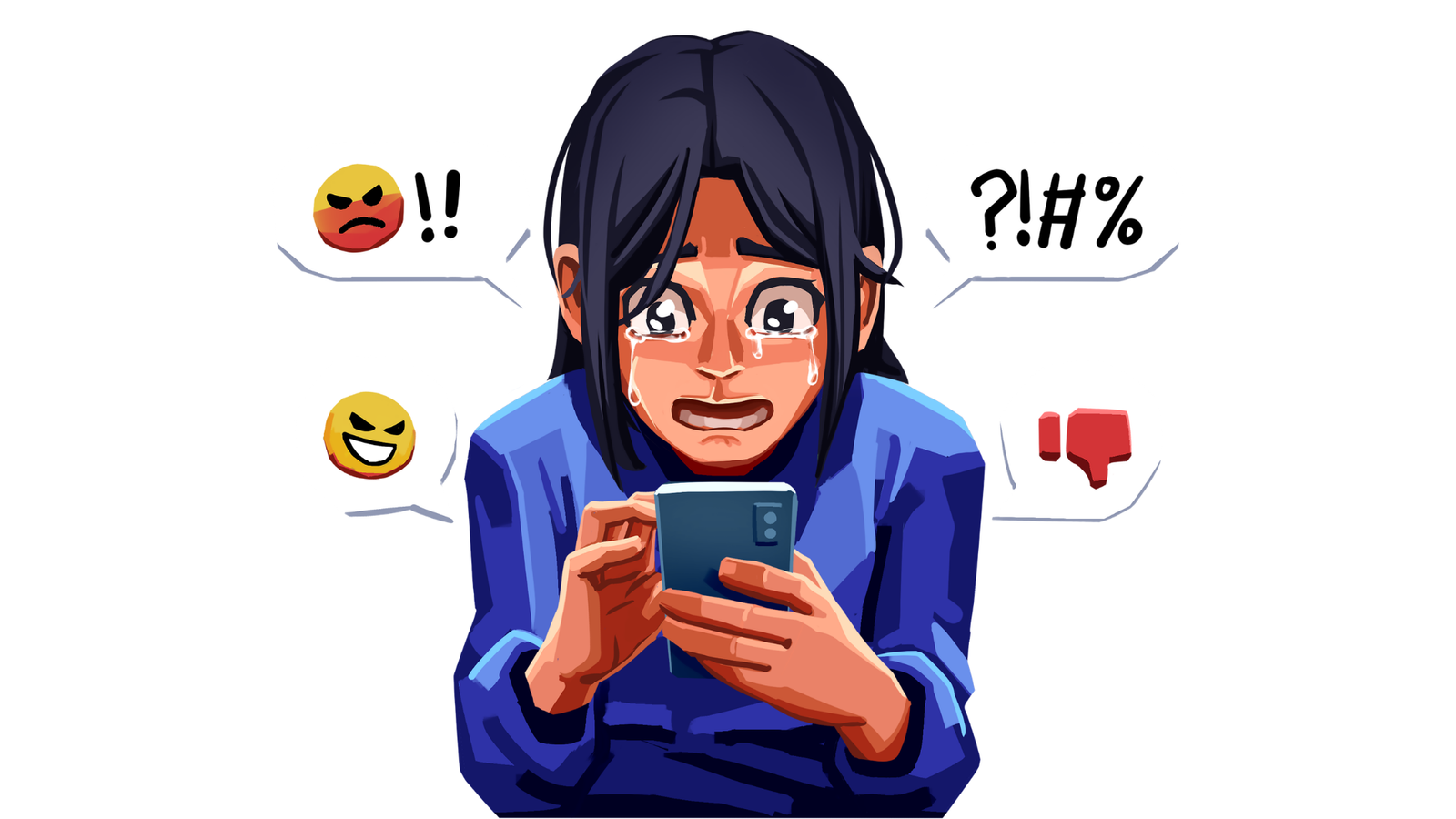Kutub.co – Banyak perempuan tumbuh dengan keyakinan diam-diam bahwa menjadi kuat adalah kewajiban. Sejak kecil, mereka diajarkan untuk menahan tangis, mengalah, mengerti keadaan, dan menjadi penopang bagi orang lain. Kekuatan itu perlahan melekat sebagai identitas hingga suatu hari, tanpa disadari, mereka lupa bahwa dirinya juga manusia yang bisa lelah.
Dalam podcast Suara Berkelas, Prilly Latuconsina membuka percakapan yang jarang diucapkan dengan jujur oleh perempuan: tentang rasa sepi yang muncul bukan karena tidak punya siapa-siapa, tetapi karena selalu dituntut menjadi tempat pulang bagi orang lain.
“Karena kadang orang-orang terdekat juga menuntut aku untuk kuat. Sehingga aku dituntut untuk hanya mendengar tapi enggak didengar. Jadi aku adalah rumah, tapi siapa rumahku? Di mana tempat nyaman yang aku juga bisa menjadi rapuh?” ungkapnya.
Kalimat itu terasa sederhana, namun menyimpan beban emosional yang berat. Banyak perempuan memahami betul rasanya menjadi pendengar setia, tempat orang lain meletakkan keluh kesah, tanpa pernah benar-benar ditanya: kamu capek tidak? Dalam posisi itu, perempuan sering kali merasa harus selalu siap, selalu ada, dan selalu kuat karena jika tidak, ia takut dianggap egois atau tidak bersyukur.
Prilly mengakui bahwa fase paling rapuh dalam hidupnya justru hadir ketika ia berada di tengah banyak orang. Sebagai figur publik, anak pertama, sekaligus sosok yang dianggap “paling bisa”, ia merasa semua orang bersandar padanya, sementara dirinya sendiri tidak tahu harus bersandar ke mana.
“Semua orang mempunyai harapannya kepada aku, tapi aku bisa berharap kepada siapa sih? Semua orang bersandar kepada aku, tapi aku enggak punya tempat bersandar. Aku dituntut untuk terus kuat, padahal aku juga ingin didengar, ingin dimengerti.”ucapnya.
Pengalaman ini mencerminkan realitas banyak perempuan yang tumbuh dalam budaya yang memuja ketangguhan, tetapi lupa menyediakan ruang empati. Ketika perempuan terlihat berhasil, mapan, atau berdaya, kesedihannya sering kali dianggap tidak valid. Seolah-olah penderitaan hanya sah dirasakan oleh mereka yang kekurangan secara materi.
“Aku sering dapat kalimat kayak, ‘Ya masih mending loh,’ atau ‘Lo nangis tapi rumah lo marmer.’ Seolah-olah kesedihan itu harus selalu dibandingkan dengan materi. Padahal sedih ya tetap sedih. Emosi itu enggak bisa diukur dari apa yang kita punya.”katanya.
Perbandingan semacam itu pelan-pelan melahirkan rasa bersalah. Perempuan mulai merasa dirinya tidak pantas sedih, tidak pantas mengeluh, dan tidak pantas lelah. Akibatnya, emosi dipendam, luka disembunyikan, dan kelelahan dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk menjadi “perempuan baik”.ujarnya.
Dalam fase yang ia sebut sebagai retak, Prilly menceritakan bagaimana kata-kata dari orang-orang terdekat justru menjadi luka yang sulit sembuh. Ia pernah dilabeli sebagai “kain pel yang lusuh” metafora tentang seseorang yang dianggap hanya berfungsi sebagai alat, bukan sebagai manusia dengan kebutuhan emosional.
“Aku ngerasa orang-orang di sekitarku berharap aku bisa terus menjadi rumah mereka, tanpa memberi tempat yang nyaman untuk pulang ke diri aku. Aku dituntut untuk kuat, mendengar, dan mengerti, tapi enggak pernah benar-benar didengarkan.”katanya.
Di titik ini, kesepian tidak lagi tentang sendirian secara fisik, melainkan tentang tidak memiliki ruang aman untuk rapuh. Banyak perempuan mengalami hal serupa: dikelilingi relasi, tetapi tetap merasa sendiri karena perasaannya tidak diberi bobot.
Perjalanan Prilly tidak berhenti di fase retak. Ia memilih masuk ke fase luruh fase yang mungkin paling sulit bagi perempuan: melepaskan. Melepaskan standar yang terlalu tinggi, relasi yang tidak memberi ruang, dan keyakinan bahwa dirinya harus selalu kuat.
“Di fase luruh, aku berusaha meninggalkan hal-hal yang sudah enggak layak lagi bersamaku. Orang-orang yang tidak memberi ruang untuk aku, standar yang terlalu tinggi, dan rasa bahwa aku harus selalu kuat. Aku menerima bahwa aku ini cuma manusia biasa.”ujarnya.
Bagi perempuan, keberanian ini sering disalahartikan sebagai perubahan yang negatif. Ketika mulai berkata tidak, ketika mulai memprioritaskan kewarasan diri, mereka dianggap berubah, egois, atau tidak lagi seperti dulu. Padahal, yang berubah bukanlah esensinya melainkan kesadarannya.
Prilly menegaskan bahwa meminta tolong dan menunjukkan kerentanan bukanlah tanda kelemahan, melainkan pengakuan atas kemanusiaan.
“Kita juga harus sadar bahwa kita tuh udah banyak memberi. Enggak apa-apa untuk sekali-sekali menerima. Minta tolong itu bukan berarti kita kalah, tapi menandakan bahwa kita manusia biasa.”pungkasnya
Dalam fase kembali utuh, Prilly tidak bicara tentang menjadi versi yang lebih sempurna, melainkan tentang menerima seluruh proses lelah, luka, dan perjuangan sebagai bagian dari hidup. Bahwa menjadi utuh bukan berarti bebas dari penderitaan, tetapi mampu berdamai dengannya.
Kisah ini menjadi pengingat penting bagi banyak perempuan: kekuatan sejati bukan tentang selalu mampu menahan semuanya sendiri, melainkan tentang keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Bahwa perempuan juga berhak punya tempat pulang. Tempat di mana ia boleh lelah, boleh rapuh, dan boleh didengarkan tanpa harus menjelaskan atau membuktikan apa pun.
Karena pada akhirnya, perempuan tidak diciptakan hanya untuk menjadi rumah bagi orang lain.Perempuan juga berhak menjadi rumah bagi dirinya sendiri.