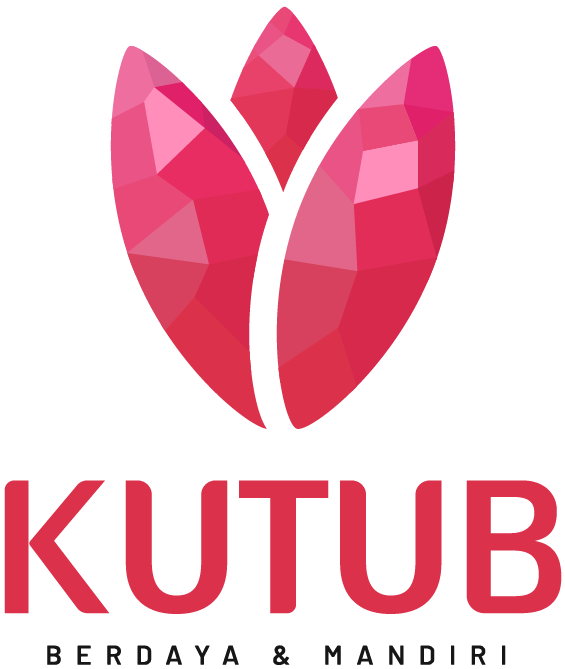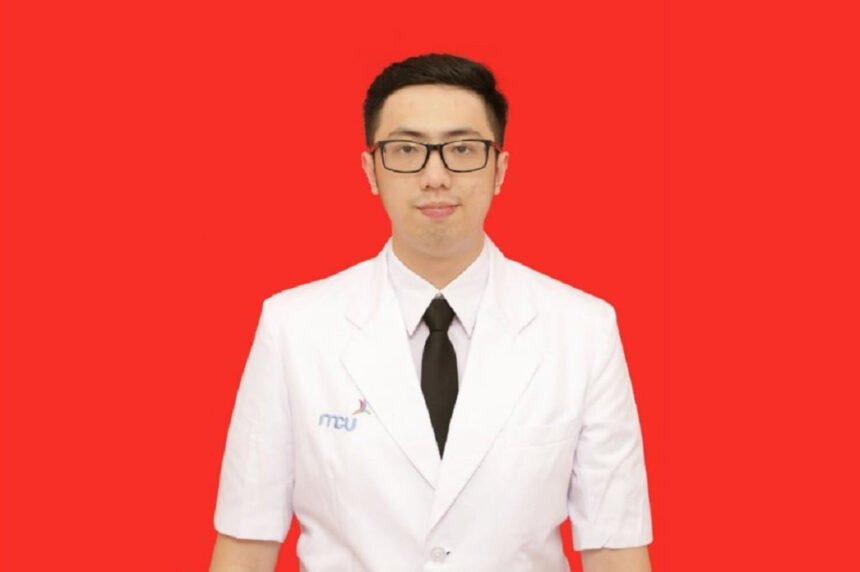Kutub.co – Kita hidup di masyarakat yang mengizinkan kelelahan, tapi tidak mengizinkan kejujuran tentang kelelahan itu sendiri.
Lelah boleh, asal tidak mengganggu ritme. Lelah boleh, asal tetap produktif. Lelah boleh, asal tidak berhenti.
Ini bukan budaya ketangguhan. Ini budaya penyangkalan.
Lelah yang dialami banyak orang hari ini bukan akibat kemalasan personal, melainkan hasil logis dari sistem ekspektasi yang berlapis dan tidak pernah dinegosiasikan. Kita dituntut berfungsi di banyak peran sekaligus anak yang berbakti, pekerja ideal, pasangan yang stabil, individu yang “bersyukur” tanpa pernah diberi ruang untuk mengatakan, cukup.
Karakter seperti Da-eun atau Jung Hye-jin menarik bukan karena dramanya, tapi karena kedekatannya dengan realitas sosial. Mereka menunjukkan satu pola yang berulang, manusia yang terlalu lama hidup dengan ukuran orang lain akhirnya kehilangan bahasa untuk membaca dirinya sendiri. Mereka tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya kelelahan struktural sedang bekerja.
Di sinilah masalah utamanya, kita kekurangan bahasa sosial untuk lelah.
Alih-alih diajari mengartikulasikan batas, kita dibiasakan menormalisasi penyangkalan. “Nggak apa-apa” menjadi kalimat wajib. Padahal itu bukan pernyataan kondisi, melainkan strategi bertahan. Dalam jangka panjang, strategi ini mahal harganya, mati rasa emosional, kelelahan kronis, dan relasi yang kosong.
Opini publik sering terjebak menyederhanakan persoalan ini sebagai isu mental individual kurang kuat, kurang iman, kurang bersyukur. Cara berpikir ini tidak hanya keliru, tapi kontraproduktif. Ia memindahkan tanggung jawab dari sistem sosial ke individu yang sudah kelelahan.
lelah bukan kegagalan personal, tapi sinyal sosial.
Artinya, ketika banyak orang merasa lelah secara bersamaan, yang perlu dievaluasi bukan mental mereka, melainkan logika hidup yang kita anggap normal. Budaya yang memuja ketahanan tanpa jeda hanya akan menghasilkan manusia fungsional yang rapuh secara psikologis.
Mengakui lelah, dalam konteks ini, bukan sekadar ekspresi emosional. Ia adalah tindakan korektif. Ia mengoreksi ilusi bahwa manusia harus selalu sanggup. Ia membuka kemungkinan relasi yang lebih jujur dengan diri sendiri dan dengan orang lain.
Kita tidak butuh masyarakat yang lebih “kuat”. Kita butuh masyarakat yang lebih jujur tentang batas.
Maka pertanyaannya bukan lagi retoris atau sentimental, melainkan reflektif sekaligus korektif:
Kapan terakhir kali kamu membiarkan dirimu lelah tanpa merasa bersalah dan apa yang perlu diubah agar itu tidak selalu terasa sebagai kesalahan pribadi?
Jika pertanyaan ini terus dihindari, kita akan terus memproduksi individu yang tampak berhasil, tapi kehilangan kapasitas paling dasar sebagai manusia, mengenali dan merawat dirinya sendiri.