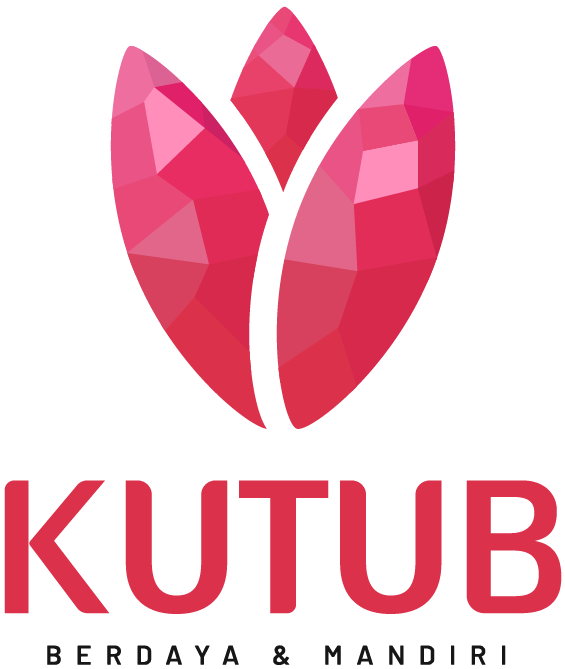Beberapa waktu terakhir, pesantren kembali jadi perbincangan publik. Di media sosial, muncul narasi yang menyamakan kehidupan pesantren dengan feodalisme bahkan perbudakan. Santri dianggap tunduk tanpa daya, kiai digambarkan sebagai pusat kuasa yang tak bisa disentuh. Tuduhan itu terdengar lantang, tetapi terasa hampa bagi mereka yang pernah hidup di dalamnya.
Sebab siapa pun yang pernah menapaki tanah pesantren tahu bahwa kehidupan di sana bukanlah ruang penindasan, melainkan jalan sunyi menuju keberkahan. Sebuah jalan yang tak semua orang mampu menempuhnya, karena berkah bukan sesuatu yang bisa dibuktikan, melainkan hanya bisa dirasakan.
Bagi sebagian orang, keberkahan terdengar abstrak—tak terukur, tak kasat mata. Tapi di pesantren, barakah justru menjadi sumber tenaga batin yang menyalakan kesabaran dan keikhlasan para penempuhnya. Ia hadir dalam hal-hal kecil: pada sapu yang digenggam santri selepas Subuh, pada langkah kaki yang mengantarkan teh ke serambi kiai, pada doa lirih di tengah malam yang tak pernah disiarkan siapa pun. Di luar tampak seperti kepatuhan, tapi di dalamnya adalah latihan batin—tazkiyatun nafs, penyucian diri yang perlahan menumbuhkan kesadaran tentang makna hidup.
KH. Hasyim Asy’ari dalam Adabul ‘Alim wal Muta’allim menulis, “Seorang guru hendaklah menghormati muridnya sebagaimana ia menghormati ilmunya, sebab ilmu tidak akan sampai kecuali melalui murid.” Dari kalimat itu kita belajar bahwa di pesantren, hubungan antara guru dan murid bukanlah relasi kuasa, tetapi relasi adab. Guru dan santri sama-sama sedang menempuh jalan ilmu; hanya posisinya yang berbeda. Kiai tidak selalu lebih tinggi, dan santri tidak selalu lebih rendah—keduanya saling membutuhkan, saling menegakkan nilai ilmu.
Begitu pula Syaikh Az-Zarnuji dalam Ta’lim al-Muta’allim mengingatkan, “Barangsiapa menuntut ilmu tanpa adab, maka ia seperti berjalan tanpa arah.” Itulah mengapa di pesantren, adab selalu didahulukan daripada kecerdasan. Sebab ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan, sementara adab tanpa ilmu justru membuka pintu keberkahan. Maka pembelajaran di pesantren bukan sekadar proses kognitif, tapi proses pembentukan diri—dari yang keras menjadi lembut, dari yang tinggi hati menjadi rendah hati.
Di pesantren, santri belajar tentang waktu dan kesabaran. Tak ada yang instan. Ilmu ditanam lewat rutinitas yang melelahkan, melalui ketaatan kecil yang mengikis ego hari demi hari. Santri mencuci piring, menimba air, menjaga tamu, atau menulis ulang catatan ngaji berulang-ulang—semuanya bukan bentuk perbudakan, melainkan khidmah: pengabdian yang melatih kepekaan dan keikhlasan. Dalam khidmah itu, santri belajar untuk tidak merasa paling tahu, dan kiai belajar untuk tidak merasa paling berkuasa.
Hal yang tampak di luar mungkin hanyalah hirarki, tapi siapa pun yang pernah menunduk di hadapan seorang kiai dengan tulus, tahu bahwa di balik ketundukan itu ada kebebasan. Di pesantren, seseorang belajar membebaskan diri dari hawa nafsu, dari kesombongan ilmu, dan dari ambisi dunia. Itulah kemerdekaan sejati yang tak bisa dipahami oleh logika yang hanya mengukur dengan angka dan jabatan.
Sebagian orang mungkin melihat sistem pesantren sebagai sisa budaya tradisional yang tak modern, tetapi justru di dalam tradisi itu tersimpan kesadaran spiritual yang lebih maju dari peradaban modern. Ketika dunia sibuk membicarakan mental health dan mindfulness, pesantren sudah sejak lama mempraktikkannya lewat zikir, muraqabah, dan kesederhanaan hidup. Pesantren bukan sistem sosial yang menindas, melainkan ekosistem spiritual yang mendidik manusia untuk sadar diri dan tahu batas.
Berkah, kata para kiai, adalah sesuatu yang tak bisa dicatat, tapi bisa mengubah hidup seseorang. Ia mungkin tak tampak, tapi terasa dalam langkah yang dimudahkan, dalam ilmu yang menghidupkan, dalam rezeki yang datang tanpa disangka. Barangkali inilah yang sulit dipahami mereka yang menilai pesantren hanya dengan kacamata struktural—karena pesantren tidak dibangun di atas kekuasaan, melainkan di atas keikhlasan.
Pesantren bukan ruang feodal, melainkan ruang spiritual tempat manusia menundukkan ego agar kelak bisa berdiri tegak di hadapan Tuhannya. Maka biarlah sebagian orang sibuk menuduh, sementara para santri tetap khidmah, tetap belajar, tetap berdoa dalam diam. Sebab jalan menuju berkah memang sunyi, tapi dari kesunyian itulah cahaya lahir dan menerangi dunia.