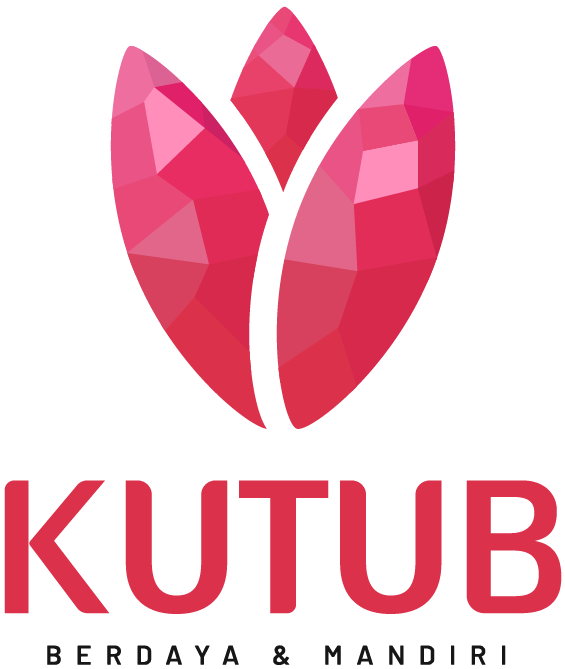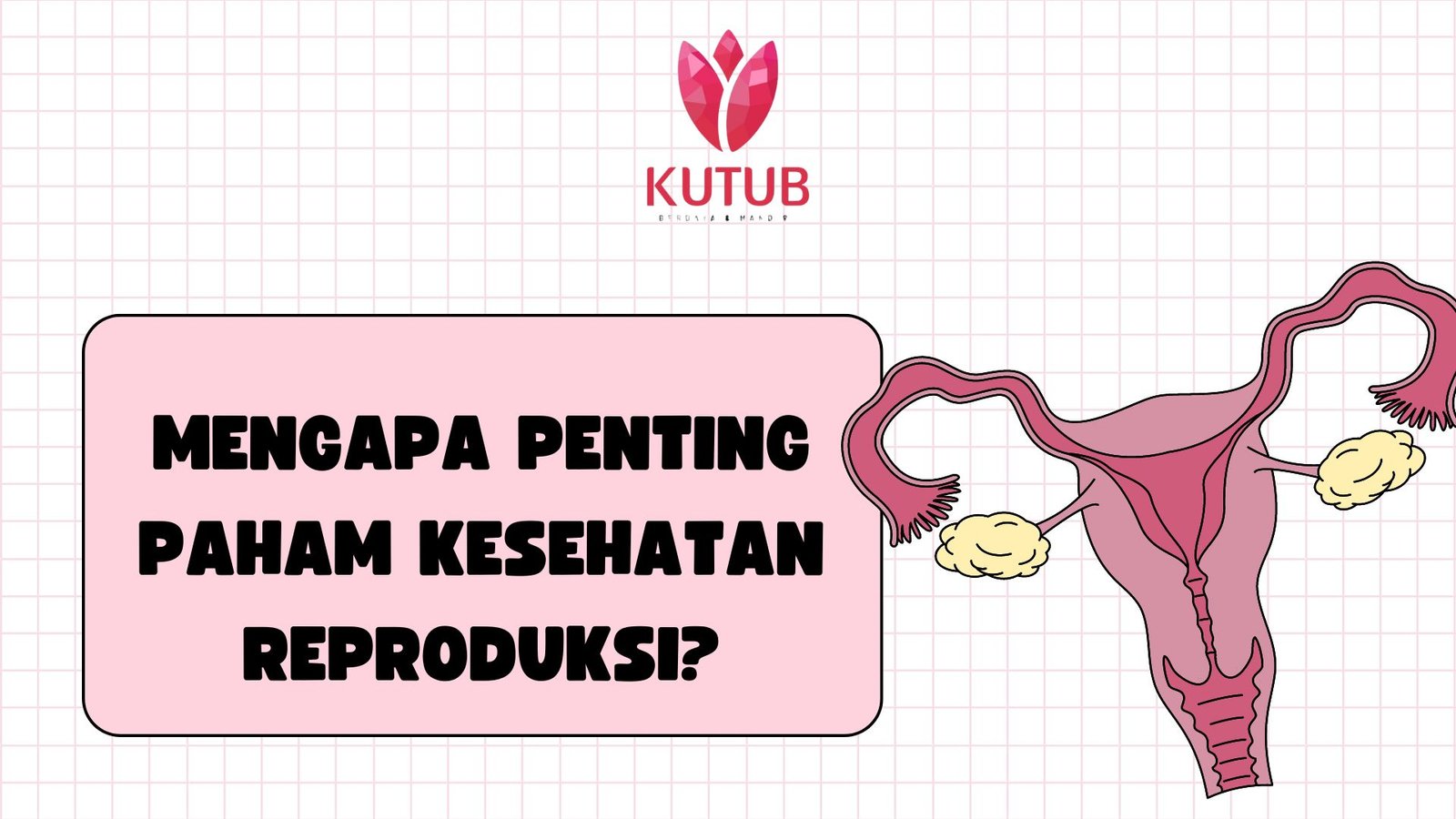Kutub.co – Ada tanggal yang berulang setiap tahun, tetapi jejak lukanya tidak ikut pergi. Rentang 25 November hingga 10 Desember dikenal sebagai 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebuah penanda yang tampak sederhana di kalender, namun bagi banyak perempuan, hari-hari itu adalah pengingat atas pengalaman yang tidak pernah mereka pilih.
Di balik spanduk kampanye dan unggahan yang memenuhi lini masa, terdapat kenyataan yang jauh lebih keras: tubuh yang mempelajari rasa takut, suara yang memilih diam, dan pengalaman kekerasan yang kerap datang tanpa suara. Kekerasan tidak selalu hadir melalui teriakan; ia bisa muncul sebagai candaan yang merendahkan, komentar yang menyudutkan, atau perhatian semu yang tidak pernah diminta.
Luka perempuan, ironisnya, kerap tumbuh di ruang-ruang yang mestinya aman rumah, sekolah, tempat kerja, hingga media sosial yang kerap memamerkan diri sebagai ruang egaliter. Yang paling menyakitkan bukan hanya lukanya, tetapi keraguan yang menyusul: korban harus membuktikan bahwa apa yang ia alami benar, seolah kebenaran hanya sah jika telah diuji dengan penderitaan tambahan.
Gerakan 16 hari tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari sejarah panjang para korban yang diabaikan, suara yang dipaksa bungkam, dan struktur sosial yang lebih cepat meragukan perempuan ketimbang menahan pelaku bertanggung jawab. Gerakan ini adalah penegasan bahwa kekerasan bukan takdir, bukan kesalahan korban, dan tidak boleh dinormalisasi sebagai “bagian dari hidup”.
Kampanye ini menuntut perubahan cara pandang yang konkret. Bukan sekadar menyebarkan poster, tetapi belajar mendengar tanpa menginterogasi; berhenti menyalahkan pakaian, sikap, atau pilihan hidup perempuan; dan menghentikan kebiasaan meremehkan batas-batas pribadi seolah itu hal kecil. Normalisasi itulah yang selama ini memungkinkan kekerasan bertahan.
Di tangan generasi muda, pesan ini bergerak lebih cepat. Jari-jari yang mengetik, layar yang tak pernah padam, dan percakapan digital yang melintasi batas ruang dapat menjadi cahaya. Namun cahaya itu hanya berarti jika keberanian turut menyertainya keberanian untuk berpihak pada korban, menegur perilaku menyimpang, dan menjaga mereka yang rentan dari penyerangan ulang.
Kekerasan tidak selalu runtuh oleh amarah yang besar. Kadang ia rapuh di hadapan konsistensi suara-suara kecil yang berdiri bersama dan menolak bungkam.
Pada akhirnya, 16 hari ini bukan ritual tahunan. Ia adalah pengingat bahwa luka yang diabaikan cenderung terulang. Dan harapannya, suatu hari, perempuan tidak lagi harus hidup dengan kewaspadaan yang dipaksakan hanya karena identitas mereka.
Setiap perempuan berhak aman tanpa syarat, tanpa jeda, dan tanpa perlu membuktikan apa pun.
Penulis: Ii Nuraeni