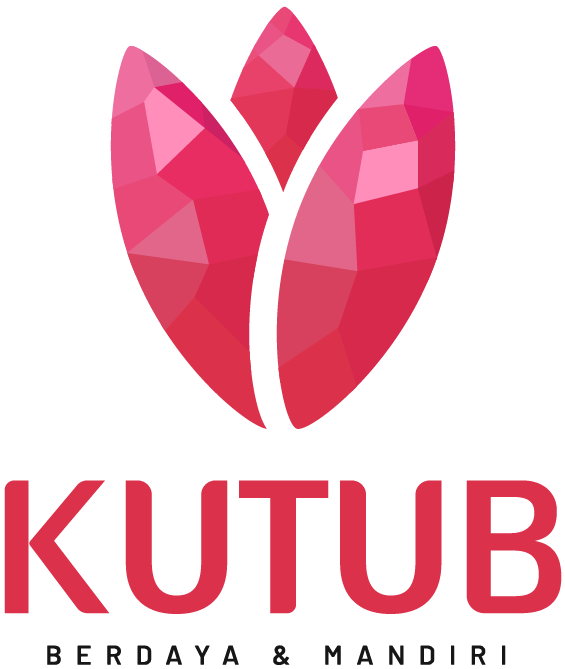Kutub.co– Risiko digital yang dihadapi anak-anak kian mengkhawatirkan. Mulai dari paparan konten seksual, ujaran kebencian, manipulasi foto berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga eksploitasi data pribadi, semuanya menjadi ancaman nyata di ruang digital. Isu ini menjadi sorotan dalam talkshow “Bangun Ruang Digital Ramah Anak #TungguAnakSiap” yang diselenggarakan Magdalene bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Jakarta Selatan, Senin (9/12).
Acara yang dihadiri sekitar 120 orang tua, guru, dan pendidik ini membahas kompleksitas tantangan digital yang dihadapi anak, sekaligus menyoroti urgensi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025.
Talkshow menghadirkan psikolog anak dan remaja Gisella Tani, influencer gentle parenting Halimah, serta Direktur Sekolah Putra Pertiwi Noviyanti Elizabeth. Ketiganya memaparkan temuan lapangan mengenai dampak langsung ruang digital terhadap anak, mulai dari tekanan psikologis hingga kerentanan terhadap kekerasan berbasis teknologi.
Tekanan Visual dan Minimnya Pendampingan
Gisella menjelaskan, media sosial kerap menciptakan standar visual yang tidak realistis bagi anak. Tekanan ini membuat mereka merasa harus tampil “sempurna” demi mendapatkan penerimaan.
“Anak-anak berpikir mereka harus terlihat seperti itu agar disukai,” ujar Gisella.
Kekhawatiran serupa disampaikan Vera, perwakilan komite yayasan sekolah swasta di Tangerang Selatan. Ia menuturkan anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP mulai tertarik mencoba perilaku tidak pantas setelah terpapar konten seksual di internet.
“Saya tidak menyangka dampaknya bisa sebesar ini,” katanya.
Cerita tersebut diamini oleh Suparto, salah satu tenaga pengajar yang hadir. Ia mencatat beragam kasus kerentanan siswa akibat penggunaan gawai tanpa pendampingan, mulai dari murid berutang demi top-up gim daring, anak SD yang mengakses konten pornografi lewat tautan YouTube, hingga siswi yang menjadi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan oleh mantan pacar. Bahkan, ia menemukan kasus manipulasi foto siswa menggunakan teknologi deepfake.
“Ada anak yang bilang, ‘Pak, saya takut ke sekolah. Saya merasa tidak aman di internet.’ Itu menunjukkan betapa rapuhnya kondisi mereka,” ujarnya.
Orang tua lain juga mengungkap adanya anak yang sampai putus sekolah akibat kecanduan gim daring. Selain prestasi akademik menurun, anak kesulitan berkonsentrasi dan tidak memiliki akses ke layanan psikologis.
PP Tunas dan Tantangan Implementasi
Gisella menegaskan, paparan konten yang tidak sesuai usia terutama tanpa pendampingan orang dewasa dapat memicu kecanduan gawai, gangguan tidur, kecemasan, hingga tekanan sosial agar selalu mengikuti tren.
“Kalau anak tertinggal tren, mereka merasa tidak dianggap oleh teman sebaya. Ini dilema besar bagi mereka,” katanya.
Co-Founder Magdalene, Devi Asmarani, menilai PP Tunas merupakan langkah awal penting, namun tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, komunitas, hingga platform digital.
Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memastikan kesiapan mental anak sebelum terjun ke ruang digital. Sementara Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, menekankan PP Tunas dirancang untuk menciptakan ruang aman bagi anak, bukan membatasi ekspresi mereka.
Di sektor pendidikan, Noviyanti Elizabeth menilai PP Tunas memberi dasar hukum yang kuat bagi sekolah untuk menyusun aturan internal, termasuk pedoman penggunaan gawai, etika digital, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan aman. Ia juga menekankan pentingnya integrasi literasi digital dalam kurikulum.
Peran Orang Tua dan Ruang Aman di Luar Layar
Halimah menyoroti pentingnya peran orang tua sebagai figur utama bagi anak. Menurutnya, orang tua perlu menjadi “influencer” pertama bagi anak melalui kedekatan emosional dan komunikasi empatik.
“Jangan langsung menghakimi atau membandingkan dengan pengalaman kita dulu. Anak perlu merasa aman untuk bercerita,” ujar pemilik akun Instagram @IGDailyJour itu.
Ia juga mendorong orang tua menyediakan waktu berkualitas, meski singkat, untuk berdialog tentang risiko konten berbahaya di internet. Menurutnya, dunia digital tidak memiliki tombol hapus, sehingga anak tidak boleh menjelajahinya sendirian.
Meski orang tua menjadi aktor utama, Halimah menegaskan perlindungan anak tetap membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
“Anak butuh ruang bermain dan bergerak di luar layar. Ruang publik yang ramah anak juga bagian dari perlindungan digital,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Novita, Ibu dua orang anak mengungkap bahwa kesadarannya terhadap risiko digital muncul ketika anaknya mulai menirukan kata kasar yang didengar dari konten daring.
“Awalnya saya pikir aman-aman saja karena cuma nonton video anak-anak. Tapi ternyata muncul iklan dan konten yang nggak pantas. Dari situ sadar, dunia digital itu banyak jebakannya kalau anak dibiarin sendiri,” tuturnya.
Dwi menambahkan bahwa ia tidak melarang penggunaan gawai sepenuhnya, namun berusaha mengatur waktu dan lokasi penggunaan agar tetap terpantau.
“HP cuma boleh di jam tertentu dan dipakai di ruang keluarga biar tetap bisa diawasi. Kadang ditanya juga, ‘Lagi nonton apa?’ atau ‘Main apa?’ Tantangannya? Anak sekarang pinter. Kalau disuruh berhenti jawabnya ‘Sebentar lagi,’ atau ngambek kalau HP diambil,” ujarnya sambil tersenyum pahit.
Menurutnya, kunci pendampingan adalah kesabaran dan konsistensi. Orang tua juga harus mau belajar teknologi, meski merasa gagap teknologi (gaptek).
Harapan ke depan, ia menilai perlindungan anak di internet butuh kolaborasi luas, bukan hanya beban orang tua.