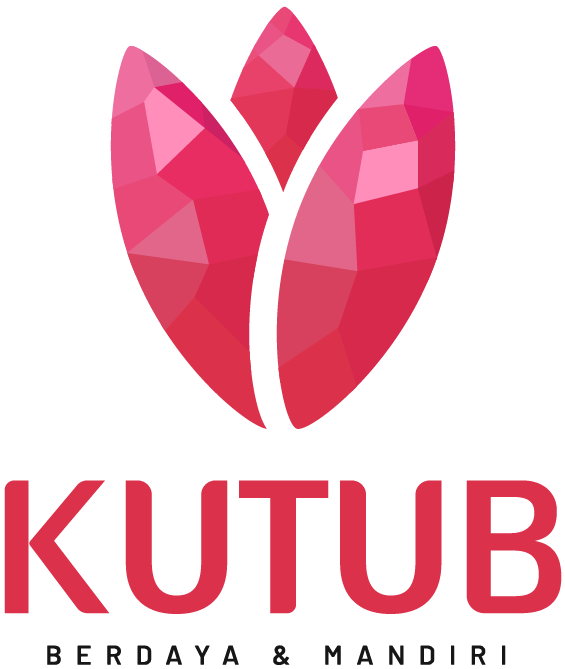Kutub.co – Di tengah arus media sosial yang serba cepat, tren busana silih berganti dari warna cerah, motif berani, hingga potongan yang nyaris eksperimental. Namun terkait batasan usia dalam berpakaian sangat jarang di bahas. Batasan ini tidak tertulis, tetapi diam-diam mengatur siapa yang “boleh” memakai crop top, siapa yang “pantas” menggunakan glitter dress, dan siapa yang “sebaiknya” memilih warna netral saja.
Fenomena ini terlihat jelas di tren TikTok Turning My Mom into Me. Video-video tersebut menampilkan momen ketika seorang ibu atau nenek berdandan ala anak muda rok ruffle, baju cerah, bahkan gaun penuh glitter. Hasilnya? Mereka tampak lebih hidup, percaya diri, dan memancarkan keceriaan. Kolom komentar pun dipenuhi pujian dan rasa haru. Namun, pertanyaan pun muncul: mengapa mereka tidak tampil seperti itu setiap hari?
Jawabannya sering kali bukan karena mereka tidak suka. Banyak perempuan, khususnya yang sudah menikah atau menjadi ibu, kehilangan ruang untuk memilih gaya pribadi. Dalam masyarakat yang masih menempatkan beban domestik dan emosional di pundak perempuan, penampilan sering kali berada di urutan terakhir prioritas. Sosiolog Arlie Hochschild menyebut ini sebagai the second shift beban kerja tak terlihat yang membuat perempuan menyingkirkan kebutuhan diri demi memenuhi peran sosial.
Melansir laman Magdalene bahwa tekanan ini bukan perkara kecil. Survei Hotter pada 2021 menunjukkan 57% perempuan merasa tertekan untuk berpakaian sesuai usia, bahkan tekanan itu muncul sejak usia 18 tahun. Semakin bertambah usia, semakin ketat pula aturan tak tertulis seperti warna terang dianggap norak, aksesoris dinilai berlebihan, crop top terlalu muda. Ironisnya, 74% perempuan mengaku lebih sering dihakimi soal pakaian dibanding laki-laki.
Sejarah turut menanamkan stigma ini. Istilah mutton dressed as lamb yang populer di era Victoria digunakan untuk merendahkan perempuan yang tampil mencolok setelah usia tertentu. Dari sanalah lahir konsep “usia ideal untuk tampil menarik” yang hingga kini masih membayangi. Psikolog mode Shakaila Forbes-Bell menegaskan, sejak kecil perempuan diajarkan bahwa penampilan adalah bagian penting dari nilai diri. Namun, saat dewasa dan tetap ingin menonjol, mereka justru dianggap tidak pantas.
Hal serupa terjadi di panggung politik. Dalam buku Women and Leadership karya Julia Gillard dan Ngozi Okonjo-Iweala, diceritakan bagaimana pemimpin perempuan lebih sering dinilai dari pakaian dan gaya rambut dibandingkan kebijakan atau keputusan mereka. Fakta ini menegaskan bahwa pakaian bukan sekadar ekspresi visual, tetapi juga arena kekuasaan. Aturan tentang siapa yang “layak” bergaya sesungguhnya adalah bentuk pengendalian terhadap agensi perempuan.
Itulah mengapa kita perlu mengubah narasi dari “gaya sesuai usia” menjadi “gaya sesuai diri”. Tidak ada yang salah dengan rok mini di usia 35, atau warna neon di usia 40. Sama seperti tidak ada usia yang terlalu muda untuk merasa percaya diri, tidak ada pula usia yang terlalu tua untuk merasa hidup.
Fesyen memang selalu berubah, namun tuntutan pada perempuan untuk tampil “pantas” seakan tak pernah usang. Kini, semakin banyak perempuan yang berani mengklaim ulang tubuh dan gayanya bukan untuk pamer, bukan demi tren, tapi demi kebebasan personal.
Pada akhirnya, pakaian terbaik bukanlah yang paling mahal atau paling sesuai tren, melainkan yang membuat kita merasa paling menjadi diri sendiri.