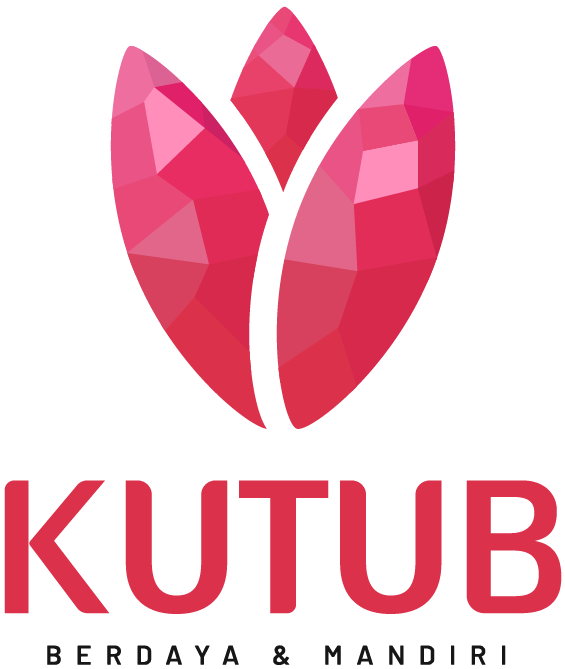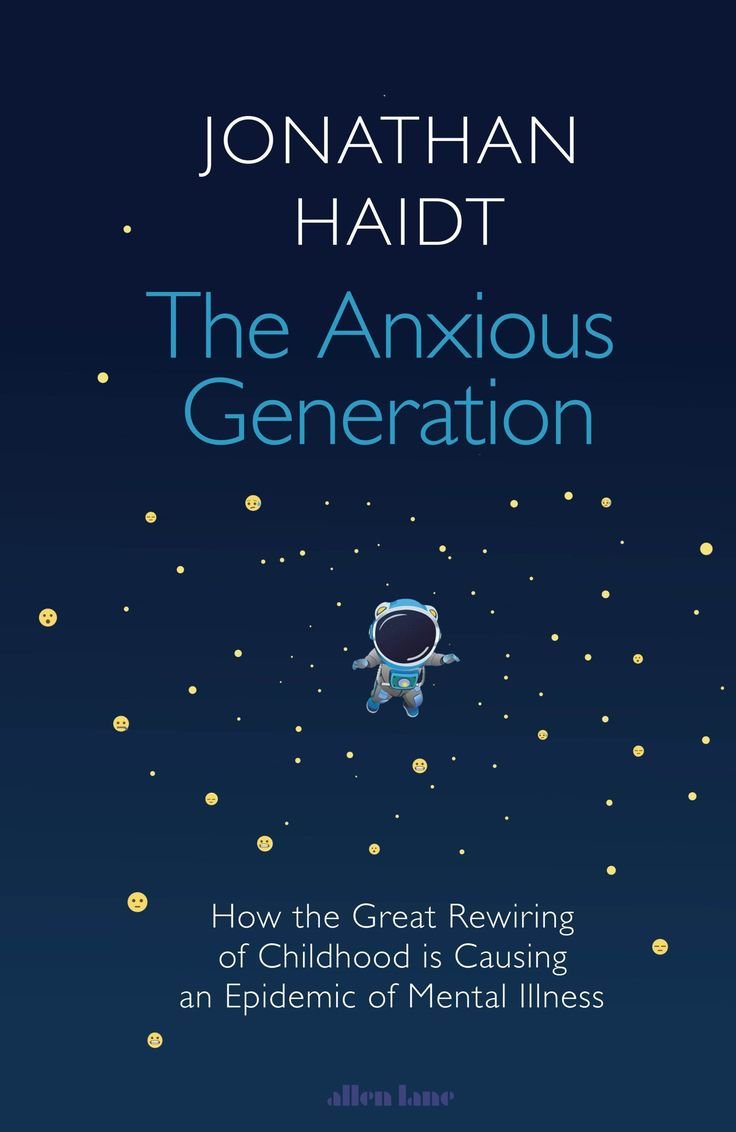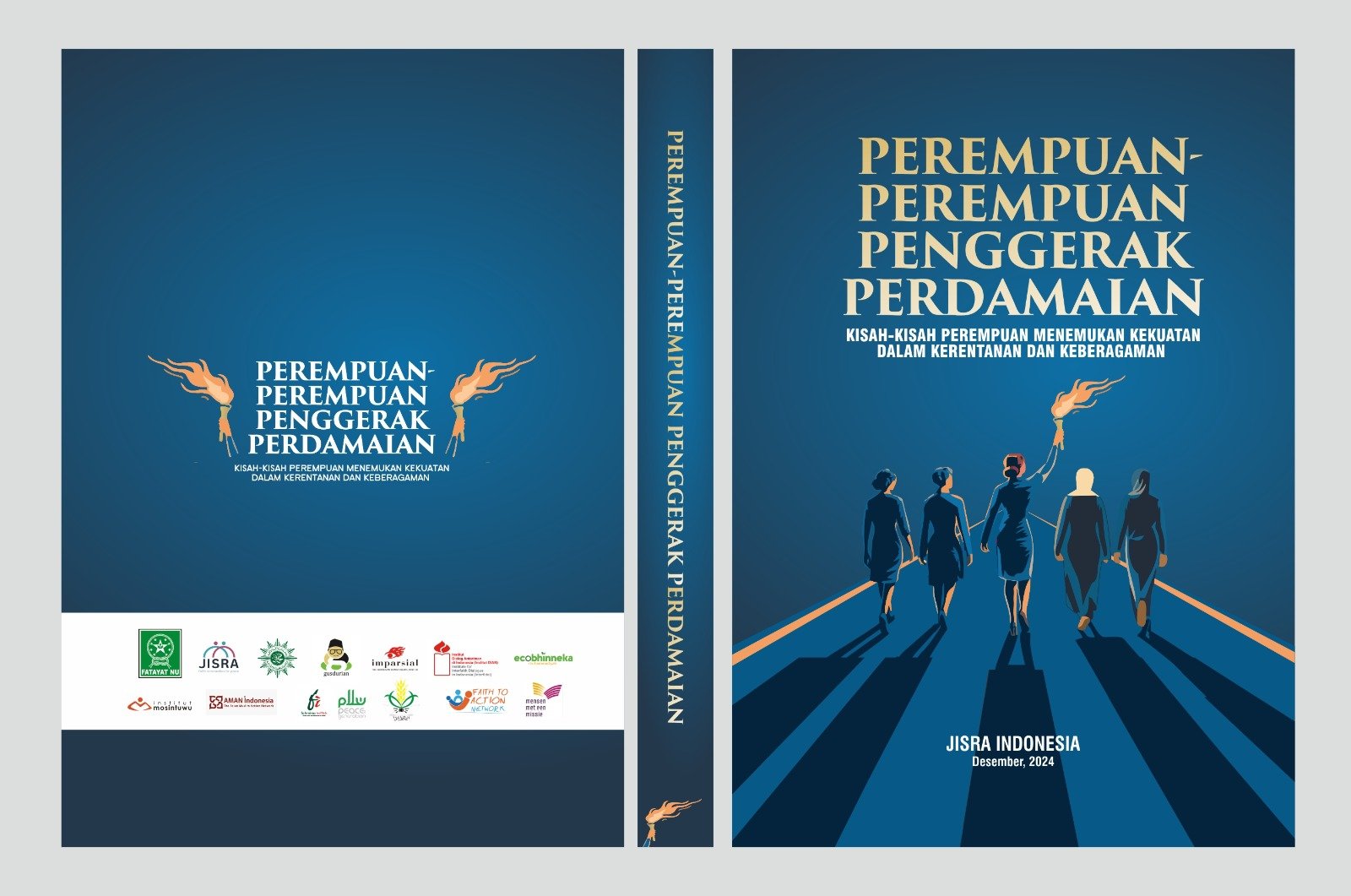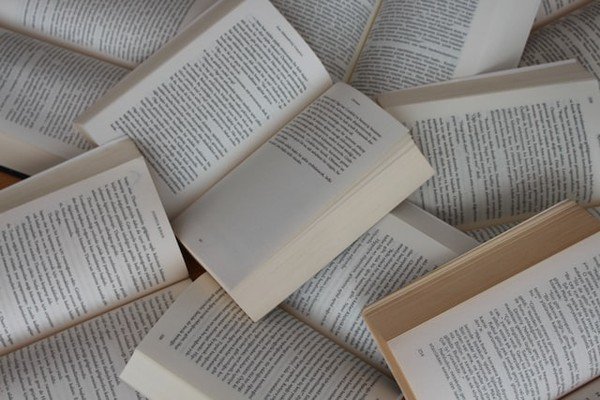Kutub.co-Di tengah hiruk-pikuk penyusunan regulasi pembatasan gawai bagi anak, satu pertanyaan mendasar jarang dibahas secara serius: apa yang sesungguhnya telah hilang dari masa kecil anak-anak kita? Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), saat ini tengah menyiapkan regulasi baru mengenai penggunaan gadget di kalangan anak usia pendidikan. Langkah ini menyusul hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang mengatur tata kelola sistem elektronik demi perlindungan anak. Upaya ini lahir dari keprihatinan atas meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dampak buruk penggunaan gawai yang tak terkendali.
Namun, perdebatan publik seputar pembatasan gawai seringkali berhenti pada soal teknologi itu sendiri berapa jam maksimal anak boleh menatap layar, usia berapa mereka boleh memiliki media sosial, atau aplikasi apa saja yang seharusnya dibatasi. Pertanyaan tentang apa yang telah digantikan oleh layar-layar itu, jarang diangkat.
Inilah yang menjadi titik tolak pemikiran Jonathan Haidt, seorang psikolog sosial yang bukunya, The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness, baru saja mengguncang diskusi pendidikan dan parenting global.
Haidt menyebut masa kecil modern sebagai masa kecil yang “terputus” terputus dari tanah, dari tubuh, dari interaksi tatap muka, dan dari risiko-risiko kecil yang dulu membentuk ketahanan anak. Ia menyebutnya sebagai “phone-based childhood” masa kecil yang didikte oleh notifikasi, scroll tak berujung, dan kebosanan yang dibunuh oleh konten cepat. Padahal, secara historis dan biologis, anak-anak butuh bermain bebas tanpa skrip, tanpa kamera, dan tanpa algoritma.
Dalam karyanya, Haidt menunjukkan bahwa lonjakan kecemasan dan depresi remaja terutama pada anak perempuan tidak terjadi secara kebetulan. Ia merujuk pada data longitudinal yang memperlihatkan hubungan antara waktu layar tinggi, terutama di media sosial, dengan peningkatan risiko gangguan mental. Namun, yang paling mengusik bukan sekadar statistiknya, melainkan ide pokoknya: bahwa kita, sebagai masyarakat, telah mencabut ruang alami anak untuk tumbuh secara wajar lalu menggantikannya dengan simulasi koneksi yang merusak.
Melansir dari laman Kemenag, Di Indonesia, respons terhadap krisis ini mulai tampak lewat regulasi. Tapi regulasi tidak bisa berjalan sendirian. Haidt menekankan perlunya gerakan kolektif, bukan hanya pembatasan. Ia menyarankan empat langkah konkret: tidak ada smartphone sebelum SMA, larangan sosial media sebelum usia 16, zona sekolah bebas ponsel, dan pemberian ruang yang luas bagi anak untuk bermain bebas secara mandiri. Solusi ini bukan tentang nostalgia, melainkan soal sains perkembangan anak.
Kita bisa belajar banyak dari semangat ini. Bukan hanya dengan melarang, tapi dengan menggantikan. Mengganti waktu layar dengan ruang bermain. Mengganti scroll TikTok dengan bersepeda di sore hari. Mengganti notifikasi dengan percakapan di dunia nyata. Mengganti pengawasan digital yang steril dengan interaksi antar teman yang tak selalu nyaman, tapi membentuk karakter.
Krisis kesehatan mental di kalangan anak bukan hanya soal kecanduan teknologi, tapi soal absennya pengalaman hidup yang mendewasakan. Pemerintah boleh membuat peraturan, tetapi keluarga dan komunitaslah yang harus menghidupkan kembali ekosistem tumbuh kembang yang sehat. Taman, lapangan, gang kecil yang aman, serta waktu luang tanpa beban prestasi semua ini adalah “alat digital” yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak kita hari ini.
Jika kita ingin Indonesia Emas 2045 tidak diisi oleh generasi yang lelah secara mental, maka mari kita mulai dari pertanyaan sederhana: apakah hari ini, anak-anak kita masih bisa bermain?