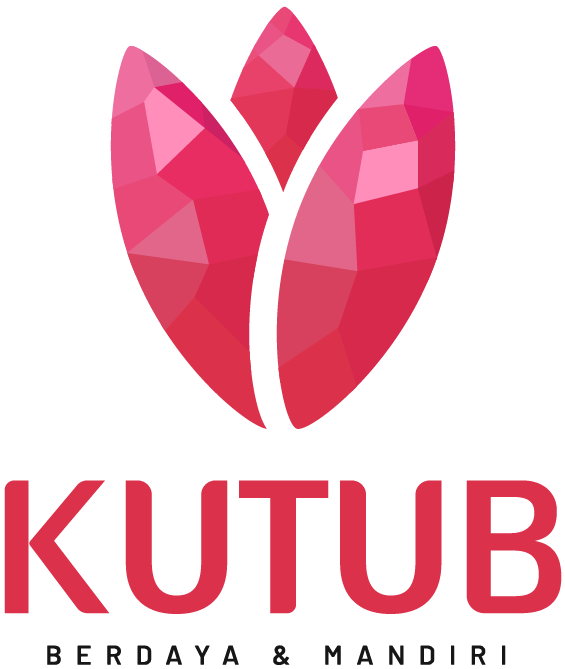Kutub.co – Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus, suara perempuan muda semakin lantang terdengar. Mereka bukan hanya berjuang untuk nilai akademik, tetapi juga membawa obor perubahan di isu-isu besar seperti kesetaraan gender dan kekerasan seksual. Dalam ruang diskusi yang sempit dan sering kali diabaikan, mereka menciptakan gerakan yang tak hanya menginspirasi, tetapi juga penuh tantangan. Siapa mereka? Apa yang memotivasi mereka? Dan bagaimana tantangan yang mereka hadapi? Artikel ini menggali cerita di balik layar perjuangan mereka.
Abil dan perjuangannya di kampus maskulin
Abil (bukan nama sebenarnya) tidak pernah membayangkan bahwa langkahnya di bangku perkuliahan akan membawanya ke dalam aktivisme yang cukup menantang. Di sebuah kampus yang identik dengan suasana maskulinitas—dari mahasiswa yang didominasi laki-laki hingga tradisi perkuliahan yang sarat stereotip—Abil berdiri sebagai anomali. Ia memilih untuk tidak tunduk pada norma yang membatasi suara perempuan.
Bukan rahasia lagi, kampus tersebut cukup maskulin dan penuh stereotip terhadap perempuan. Dalam perkuliahan sendiri, Abil jarang menemukan diskriminasi dari pihak pengajar, namun, terkadang diskriminasi tersebut datang dari kawan-kawannya melalui selentingan yang seksis. Adapun ketika ingin mendaftar dalam proyek-proyek di luar mata kuliah, Zahra sering ditolak karena pimpinan proyek dan jajarannya lebih memilih laki-laki. “Susah nanti perempuan mah,” kata Abil mengutip komentar pewawancara proyek.
Langkah pertamanya memasuki kegiatan perjuangan perempuan dimulai atas ketertarikannya terhadap isu perempuan saat SMA, namun dikarenakan sekolah asrama yang membatasi, ia baru mengikuti isu perempuan dan kesetaraan ketika ia memasuki dunia perkuliahan. Perjalanannya dimulai ketika ia mengikuti sebuah organisasi non-pemerintah lokal kampus yang bernama HopeHelps ITB, kesenatoran dari Program Studinya, juga menjadi anggota Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual ITB dalam bidang penanganan.
Sebagai anggota Satgas PPKS, Abil menemukan tantangan dalam penanganan kasus, tepatnya ketika ia mendiskusikan kasus. Baginya, kekurangan pengetahuan tentang hukum, psikologis dan lain sebagainya menjadi hambatan yang cukup khas. Selain itu, hambatan juga terjadi dikarenakan satgas PPKS hanya berfokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menyebabkan beberapa kasus yang terjadi di luar pendidikan, pengajaran dan pengabdian tidak dapat ditangani. Untungnya, Abil juga merupakan bagian dari HopeHelps, sehingga kasus-kasus di luar penanganan satgas PPKS dapat ditangani mereka. “Aku berharap, satgas PPKS kedepannya bisa menangani kasus di luar kegiatan Tri Dharma dengan jelas dan tanpa pertimbangan.” tegasnya.
“Perspektif anggota satgas juga masih ada yang patriarkis”. Abil bercerita. Walaupun keanggotaan satgas PPKS dipilih dengan transparan dan melalui uji publik, namun, ada beberapa anggota yang belum mendapatkan pendidikan penanganan KS yang berakibat pada perspektif mereka dalam menangani kasus.
Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Abil dan organisasinya berusaha menciptakan ruang aman dengan melakukan propaganda-propaganda serta sosialisasi, diskusi, dan lainnya mengenai kekerasan seksual dan ruang aman melalui media sosial dan kegiatan tatap muka.
Melawan maskulinitas di kampus yang identik dengan laki-laki, Abil menunjukkan resiliensi perempuan untuk tembus dan berkontribusi di bidang STEM dengan tetap membangun ruang aman dan bebas kekerasan seksual yang jarang dilirik oleh kawan mahasiswa ITB lainnya. Tidak hanya berhenti di kampus saja, perjuangannya ini akan dia teruskan hingga masa depan, dengan lebih terstruktur dan sistematis.
Terbenam dalam stereotip, bersinar dalam perlawanan: Kisah Matahari di kampus Islam
Matahari memulai perjalanan aktivismenya dari pengalaman sebagai penyintas. Setahun sebelum berkuliah di universitas tersebut, menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus sebelumnya, namun kasus tersebut tak pernah mendapat keadilan. Matahari tidak menerima penindasan yang dialaminya, sehingga menjadi pemantik semangatnya untuk bertindak dan memenuruskan perlawanan Kekerasan terhadap perempuan, tetapi insiden itu menjadi pemantik semangatnya untuk bertindak.
Di lingkungan yang sarat dengan tradisi dan nilai konservatif, Matahari berdiri tangguh membakar harapan. Sebagai seorang mahasiswi dan aktivis di sebuah universitas Islam, Matahari menghadapi tantangan yang tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam komunitasnya sendiri. Ia terjebak dalam stereotip yang menganggap perempuan harus “tahu batas,” namun perlahan, ia bangkit dan menjadi cahaya bagi perjuangan melawan kekerasan seksual di kampus.
Melangkah dari pengalaman sebelumnya, ia memutuskan untuk berkuliah di kampus baru dan mencari kegiatan-kegiatan yang dapat ia ikuti sebelum mendaftar. Pilihannya jatuh pada sebuah kampus Islam di luar kota tinggalnya. Kampus itu memiliki sebuah unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang berfokus pada isu gender dan kekerasan seksual (KS) yang bernama Women Studies Centre.
Perjalanan aktivisme bersama Women Studies Centre menjadi aktivisme pertama dan melanjutkan keterlibatan dengan menjadi anggota Bilik Pengaduan, sebuah Badan Semi Otonom dari UKM Women Studies Centre (UKM WSC). Memahami mengenai perjuangan untuk menyuarakan hak-hak penyintas KS, ia meniti perjalanan perjuangannya hingga kini menjadi Koordinator dari Bilik Pengaduan. Bekerja sama dengan banyak organisasi lain di luar kampus, Matahari memupuk dan memperjuangkan korban dari dalam dan luar kampus.
Berkuliah di kampus Islam, Matahari dan mahasiswi lainnya sangat dibatasi. Perempuan dipaksa untuk menggunakan pakaian yang dianggap ‘sopan’ oleh kampus, menutup aurat, berhijab panjang hingga pembatasan beberapa penggunaan model celana dilakukan. Peraturan yang kemudian cukup menyulitkan dalam penanganan kasus KS. Korban KS tersebut selalu dibenturkan dengan narasi yang menyalahkan cara berpakaian korban, bahkan klausul ‘pakaian’ dituliskan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, tepatnya dalam ‘pedoman pencegahan kekerasan seksual.’
“Soal cara berpakaian, sampai adanya ‘verifikasi kasus’ yang kadang mempertanyakan history hubungan korban yang gak relevan dengan penanganan kasus.” Jelas Matahari membicarakan mengenai penanganan kasus dari sisi kampus. Verifikasi kasus, menurut Matahari, juga menunjukkan sikap timpang pihak kampus dalam penanganan KS yang tidak menunjukkan keberpihakannya pada korban. Baginya, kasus bisa langsung dilakukan pendampingan tanpa ada verifikasi terlebih dahulu, namun, keberpihakan dan perspektif kepada korban yang berbasis empati dan etika feminisi perlu diutamakan.
Percobaan peretasan akun sosial media yang digunakan untuk penanganan kasus juga menjadi ancaman. “Dulu hotline [pengaduan] itu pakai nomor pribadi, jadi rentan mendapatkan upaya peretasan atau pengancaman, untungnya gak berhasil.” Matahari membagikan pengalamannya ketika penanganan kasus hingga akhirnya diputuskan untuk membuat hotline baru yang tidak terhubung dengan akun pribadi.
Tantangan-tantangan lainnya juga datang dari budaya kampus yang penuh dengan politik antar organisasi ekstra yang mengancam regenerasi WSC itu sendiri. Status keanggotaan di WSC dijadikan sebagai batu loncatan agar mendapatkan jabatan lebih tinggi di organisasi ekstranya tanpa berkontribusi aktif dalam penanganan kasus maupun kegiatan WSC lainnya. Matahari sendiri pernah mendapatkan black campaign yang dilakukan oleh organisasi ekstra agar dijatuhkan dan anggota organisasi tersebut bisa dilantik menjadi ketua atau menjabat di WSC.
Glorifikasi sosok dan jabatan juga menghalangi penanganan kasus yang optimal, karena sosok-sosok tersebut, baik mahasiswa maupun dosen, seringkali dilindungi organisasi dan tetap melela di kampus. “Ada pelaku KS yang masih dikasih panggung, bahkan, ngisi materi tentang hukum dan kekerasan seksual.” Keluh Matahari.
Kisah Matahari adalah bukti bahwa di tengah stereotip dan diskriminasi, perjuangan perempuan dapat menjadi cahaya yang menembus kegelapan. Baginya, perlawanan terhadap kekerasan seksual bukan hanya tentang memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga tentang menciptakan budaya yang menghargai dan melindungi martabat perempuan.
“Seperti matahari, kita mungkin terbenam dalam stereotip, tapi suatu saat kita pasti bersinar di tengah perlawanan,” tutupnya dengan optimisme yang tak tergoyahkan.
Penulis: Dion
Artikel ini merupakan kolaborasi liputan bersama Women’s Media Collabs, didukung oleh IMS – International Media Support dan European Union