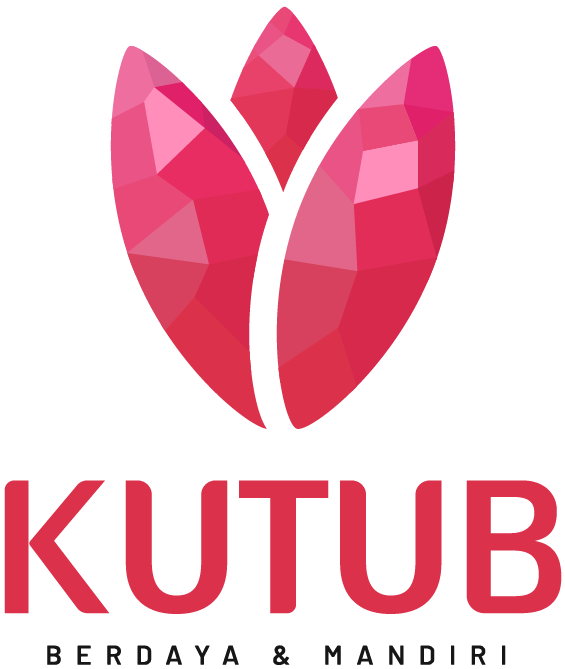Kutub.co – Luka yang paling dalam sering kali tidak meninggalkan bekas di kulit. Bagi Aurélie, penjara itu dimulai di usia 15 tahun bukan dengan besi melingkar di tangan, melainkan dengan perhatian yang perlahan-lahan berubah menjadi jeruji besi. Dalam narasi ini, kekerasan tidak selalu meninggalkan lebam biru; kekerasan yang paling mematikan justru datang dari luka yang tidak terlihat. Melalui memoar Broken Strings, kita diajak melihat bagaimana “asmara” dipersenjatai untuk melumpuhkan logika dan bagaimana teknologi berubah menjadi borgol digital yang membungkam suara. Kisah ini bukan sekadar curahan hati seorang selebriti, melainkan alarm mengerikan tentang kontrol koersif, sebuah bentuk kekerasan yang bekerja dalam senyap, namun sanggup merampas agensi seseorang hingga ke titik nol. Tulisan ini membedah bagaimana mekanisme kontrol tersebut bekerja dan mengapa narasi Aurélie harus menjadi alarm keras bagi literasi kesehatan mental kita hari ini.
Selama ini, masyarakat cenderung mendefinisikan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) hanya pada serangan fisik yang kasat mata. Jika tidak tampak memar, tidak ada luka, atau tidak ada jeritan minta tolong, maka hubungan dianggap baik-baik saja. Namun, narasi Aurélie dalam Broken Strings menegaskan bahwa kekerasan bisa terjadi dalam senyap; ia bukan terletak pada agresi fisik, melainkan pada perampasan kemandirian secara sistematis. Evan Stark, dalam teorinya tentang Kontrol Koersif, menjelaskan bahwa pola ini lebih mirip dengan penyanderaan di tempat terbuka. Pelaku tidak perlu menggunakan tangan untuk memukul jika ia sudah biasa menggunakan rasa takut untuk mengatur.
Dalam kasus Aurélie, kita melihat bagaimana pelaku mulai memutus jembatan komunikasi Aurélie dengan dunia luar, termasuk keluarga dan rekan kerja. Pelaku mulai melakukan mikromanajemen kehidupan; segala aspek, mulai dari jadwal syuting hingga cara berpakaian diatur untuk memastikan bahwa otoritas berada di tangan pelaku. Borgol digital ini mencapai puncaknya ketika pelaku menggunakan ancaman penyebaran konten intim sebagai alat sandera psikis, sebuah bentuk teror yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan selain tunduk demi menyelamatkan reputasi dan masa depannya. Pengawasan ponsel tidak luput dari kontrol koersif pelaku, menyebabkan korban kehilangan ruang privat bahkan di dalam pikirannya sendiri.
Tragisnya, keadaan tersebut menempati posisi normalisasi sosial di bawah payung patriarki; perilaku posesif berlebih sering kali dikemas dengan pita merah jambu berlabel “sayang”, “protektif”, atau “kepedulian”. Masyarakat telah terlanjur memaklumi belenggu tersebut sebagai dinamika asmara remaja yang lumrah. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan psikis dan kontrol koersif merupakan bentuk KDP yang paling sulit dibuktikan secara hukum, namun memiliki dampak trauma jangka panjang yang setara dengan kekerasan fisik. Pertanyaan yang paling sering dilontarkan kepada korban adalah, “Kenapa tidak pergi saja?” Kita perlu memahami bahwa hubungan tersebut merupakan sebuah siklus kekerasan yang berputar secara berulang dan manipulatif.
Permohonan maaf dan kasih sayang yang intens setelah kekerasan bertindak layaknya racun berbalut madu. Secara psikologis, ini memicu fenomena Trauma Bonding, sebuah ikatan emosional yang kuat antara korban dan pelaku. Aurélie, seperti banyak remaja lainnya, terperangkap dalam harapan bahwa sosok “baik” adalah jati diri pelaku yang sebenarnya, sementara kekerasan hanyalah bentuk kekhilafan.
Kisah dalam Broken Strings bukan sekadar catatan kelam masa lalu seorang selebriti, melainkan cermin bagi ribuan remaja saat ini yang mungkin terjebak di dalam labirin serupa. Langkah awal untuk memutus rantai ini adalah dengan membangun literasi kesehatan mental yang mumpuni, terutama dalam mengenali sinyal bahaya atau red flags sejak dini. Pelajaran terpenting dari keberanian Aurélie adalah pemahaman bahwa “perlawanan dimulai dari suara”. Kisah Broken Strings memberikan harapan bahwa sesunyi apa pun suara kita saat terjerat, selalu ada jalan untuk pulang ke diri sendiri. Bagi masyarakat, tugas kita adalah memastikan bahwa ketika seorang remaja berani bersuara, kita tidak membalasnya dengan penghakiman, melainkan dengan tangan yang siap merangkul dan telinga yang siap mendengar.
Kekerasan dalam pacaran adalah urusan publik, bukan masalah privat yang harus diselesaikan di balik pintu tertutup. Mari kita jadikan narasi Aurélie sebagai titik balik. Sudah saatnya kita menajamkan perhatian terhadap red flags yang tersembunyi dan memperkuat telinga untuk mendengar suara-suara yang terbungkam. Sudah saatnya senar yang rusak itu diputus, agar lagu baru tentang kemerdekaan diri bisa mulai dinyanyikan.
Penulis: Gina Rhahmawati